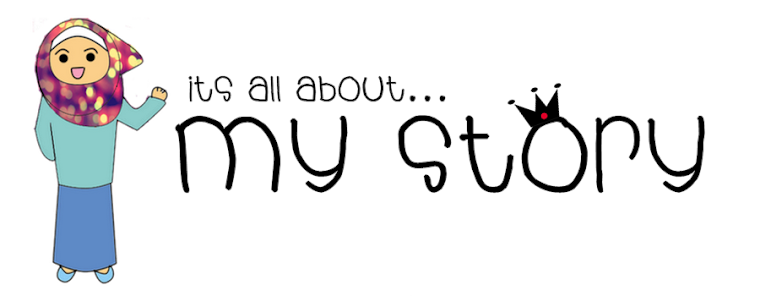RIMBA
kian
suram. Berisik daun-daun mulai mengerikan. Aroma masakan kentang semakin pekat
menusuk hidung. “Lekas temukan jalan keluar, Sayang.” Seorang perempuan berkata
kepada kekasihnya. Lututnya gemetar, dari leher di balik kerudungnya, keringat
mengalir deras. Ia ketakutan.
Kekasih diam saja, ia
putus asa. Sedari tadi, sejak azan asar
berkumandang dari kejauhan, mereka sudah tujuh belas kali berputar di tempat
yang sama. Di jalanan yang sama. Dan, langit mulai gelap. Tak ada yang bisa
didengarkan selain bunyi-bunyi mengerikan khas penghuni rimba. Dan, aroma masakan
kentang semakin menguat. Mereka berpagutan.
Menjelang tengah malam,
mereka tertidur dengan alas dua tas ransel besar. Tidak ada gairah pada
keduanya. Mereka tertidur dalam kelelahan, lelah yang menyedihkan. Kekasih
bermimpi, bukan mimpi basah. Ia didatangi seorang Dewa Perempuan. Parasnya
cantik, rambutnya bergelombang menutupi buah dadanya yang sintal. Sekali lagi, Kekasih tidak mimpi basah.
Keringatnya semakin deras dalam ketakutan.
Kekasih mengangkat kakinya
perlahan, menjauh dari Dewa Perempuan. Kakinya berat, sangat berat. Dewa
perempuan itu masih saja tersenyum. Senyumnya mengerikan, senyum yang membunuh.
Kekasih berusaha sekuat tenaga mengambil jarak, dan ia lupa, tadi, sebelum Dewa
Perempuan datang, ia sedang bermesraan dengan perempuannya. Dan, ia sudah
kabur, tapi perempuannya tak ikut. Kekasih menghentakkan kakinya, “Sial!
Perempuanku tertinggal bersama Dewa Perempuan.”
Kekasih ingin kembali,
menjemput perempuannya. Dari dalam rimba yang sangat kelam, ia mendengar
jeritan perempuannya. “Kasih, kasih! Di mana engkau? Jemput aku. Dewa Perempuan
mulai memakan tubuhku. Kelingking kakiku sudah lenyap separuhnya, Kasih. Kasih,
di mana engkau? Kasih!” tuturan yang mengerikan. Perempuannya berteriak dengan
nada penuh kesakitan. Kekasih benar tidak sampai hati, ia ingin menjemput.
Ingin sekali. Tapi, di depannya sudah ada pintu rimba, pintu menuju jalan ke
luar. Pintu yang mengantarkkannya pada keluarganya. Ibunya yang menenun sarung,
dan ayahnya yang mencangkul sawah.
Kekasih berdoa, ia
memohon dijalankan pada keputusan baik.
Kekasih membantu Ayah
mencangkul. Pada malamnya, ia melipat kain-kain tenunan Ibu. Kekasih baru akan
tidur setelah orang rumah tertidur. Ia akan terus bekerja selagi masih ada yang
terjaga. Kekasih menjadi tidak pernah lelah. Energinya tidak habis-habis, semua
yang berat-berat, ia angkat. Semua yang sulit-sulit, ia pecahkan. Kekasih
menjadi omong-omongan di kampung, pemudi-pemudi di sana mulai mencari cara
menarik hatinya.
Kekasih tidak tahu,
bahwa di dalam rimba, masih tertinggal perempuannya yang sekarang hanya tinggal
kepala. Lehernya ke bawah sudah dinikmati Dewa Perempuan. Dan, Kekasih juga tidak tahu, bahwa
hidupnya menjadi luar biasa setelah menumbal perempuannya pada Dewa Perempuan
itu. Kekasih menjadi tidak tahu apa-apa. Ia hanya berjalan, bekerja, dan
bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya. Kekasih
menjadi lugu.
Sekarang pada setiap
pagi pemudi-pemudi desa bersolek di kaca riasnya. Malam harinya mereka memasak
gulai kambing, dan pada siangnya mereka berkunjung ke rumah Kekasih. Mereka tidak
pernah mendapati Kekasih sedang ada di rumah.
Pemudi-pemudi desa
mengubah jadwal bertamunya. Pada pagi hari mereka memasak, siangnya bersolek,
dan malamnya berkunjung ke rumah Kekasih. Dan, mereka menemui Kekasih dan
keluarganya sudah tertidur. Mereka tidur di ruang depan dengan pintu terbuka.
Tidur mereka, membentuk formasi segitiga berantakan, begitu setiap malamnya.
Dan, untuk terakhir
kalinya, pemudi mencoba mengganti jadwalnya kembali. Pada siang hari mereka
memasak, malamnya bersolek, dan pagi hari mereka bertamu ke rumah Kekasih.
Mereka berhasil! Ibu Kekasih
sedang menenun sarung, dan Kekasih sedang melipat-lipat kain. Tapi mereka tidak
menemukan Kekasih seperti yang dikatakan orang-orang kampung. Tidak ada lelaki dengan
lesung pipit dalam dan senyum menawan di sana. Di samping Ibu yang sedang
melipat-lipat kain, hanya ada lelaki berbulu lebat, tingginya tak sampai 100
meter. Tatapan matanya kosong, ia melipat sambil sesekali menggaruk dada dan
betisnya yang berbulu lebat itu.
Pemudi-pemudi ingin
lari, mereka merinding.
***
Rimba sudah kosong,
tidak ada jeritan perempuan yang minta dijemput. Aroma masakan kentang goreng sudah
tidak tercium. Orang-orang sudah berani datang ke rimba lagi. Mereka mencari
kayu, mencari tanaman, dan apa saja yang bisa memberi kehidupan.
Menyedihkan! Mereka
tidak menemukan pemberi kehidupan di rimba. Sama seperti alur pada kunjungan ke
rimba sebelumnya, mereka tertidur kemudian bermimpi bertemu Dewa Perempuan.
Bagi mereka yang memilih jalan pulang, sampailah mereka di rumahnya
masing-masing. Dengan ayah,
ibu,
dan sanak saudaranya. Meski, sepulang dari rimba mereka juga mengerdil dan
berbulu lebat.
Kampung kembali rusuh.
Kali ini, seorang janda
berparas oriental menangis histeris di depan balai. Ia memukul-mukul teras balai dengan kepalan tinjunya.
Telapak tangannya menjadi lebam.
Orang-orang
beramai-ramai mengerumuninya, mereka membentuk lingkaran dengan Si Janda berada
di porosnya. Mereka saling berbisik, saling berprasangka. Dari mulut Janda,
terdengar umpatan-umpatan yang tidak jelas, samar sekali. Janda masih saja
memukul-mukul teras balai
dengan tangannya yang sekarang mulai berdarah.
Dari balik kerumunan
orang-orang yang bergunjing, keluarlah Kekasih dengan pakaian hitam menutupi
sekujur tubuhnya yang berbulu lebat. Ia bersujud di kaki Janda. Orang-orang
terperangah, semesta semakin gila, mereka mengurut-ngurut dada.
Janda menatap
lekat-lekat pada mata Kekasih. Ia menemukan sepasang mata balam dengan sinar
yang hilang. Ia mendekat, lebih dekat, dan lekat. “Tak salah lagi! Di mana
putriku, He?” Janda berteriak keras sekali. Suaranya menggema ke seisi balai.
Lingkaran melebar, orang-orang agak menjauh. Takut jika tiba-tiba Janda
mengamuk dan menerkam mereka.
“Ampun, Janda. Putrimu
tertinggal di rimba. Ia dimakan Dewa Perempuan.” Kekasih semakin kuat sujudnya,
ia mencium kaki Janda.
Janda kembali menangis.
Darah di tangannya semakin deras. Orang-orang bubar, mereka buru-buru ke dukun,
meminta petunjuk atas kejadian yang menimpa kampungnya.
Di balai, Kekasih mematung dalam
sujudnya kepada Janda.
Menjadi dukun di
kampung tidak gampang, kau setidaknya harus hapal ayat-ayat di kitab. Karena,
selera orang-orang kampung ini lain, mereka mendudukkan dukun sebagai tukang
baca ayat-ayat.
Setelah menghafal ayat, kau akan dijadikan Tuhan
ke dua oleh mereka. Percayalah, selepas itu, uang tidak akan berhenti mengalir
kepadamu.
Dukun membaca
ayat-ayat, lalu bernarasi dengan nada seperti orang dicekik.
“Ah, tidak. Tidak! Ada
sepasang kekasih bermesraan di rimba. Mereka berpagutan, bericuman, lalu
menjadi satu. Mereka tidak tahu, di rimba itu, ada sepasang mata dewa yang
cemburu. Dewa Perempuan! Ya, ya!”
“Kalian
tahu? Dewa Perempuan itu mulai rusuh. Disuruhnya daun-daun di rimba bergesekan
menimbulkan suara gaduh. Lalu, pelan-pelan, ia mengirim doa jahat kepada
sepasang kekasih. Mereka tertidur. Dan, Dewa Perempuan membawa lari satu di
antara mereka.
“Sebentar-sebentar,
aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang dibawa lari oleh Dewa Perempuan
itu.” Dukun mulai terbatuk-batuk. Salah satu dari penduduk kampung menyuguhinya
minuman.
“Oh, si wanita rupanya.
Dari balik cengkeraman
Dewa Perempuan, aku melihat kerudung putih terjulai.”
“Lalu ke mana perginya
si lelaki, Dukun?” seorang bujangan dengan nada ingin tahu meracau tanpa izin.
Dukun geram
imajinasinya dilangkahi. “Lelaki kembali ke rumahnya. Ia tidak mengurusi
perempuannya lagi.” Dukun menyelesaikan narasinya.
Orang-orang kampung
pintar sekali membuat kegaduhan. Usai dari rumah Dukun, mereka kembali ke balai. Mereka merasa sudah cukup
mendapat bantuan dari Dukun.
Di sana, Janda dan
Kekasih mematung. Suara tangisan Janda sudah tidak terdengar. Seorang lelaki
yang tadinya bertanya kepada Dukun mengambil posisi berdiri di depan Janda.
“Anakmu diculik Dewa
Perempuan. Kekasih tololnya ini, tidak menghalangi Dewa Perempuan ketika ingin
menculik anakmu. Mereka dalam persetubuhan yang hina.”
Kekasih berdiri,
ditatapnya dalam-dalam manik mata laki-laki yang berdiri di hadapan Janda.
Tiba-tiba dari dalam balai yang sedari tadi hening,
keluar seorang lelaki dan perempuan dengan sarung menutupi belahan dadanya.
Bulu-bulu pada sekujur tubuh Kekasih hilang, ia tidak lagi kerdil. Diumpatnya
perempuan dengan sarung di dada itu.
“Aku mencarimu hampir
gila, Sundal.”
Sleman,
28 Januari 2014